Kejati Sulsel Inisiasi Seminar Ilmiah: DPA Sebagai Kunci Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset
“Prinsip Dominus Litis, yang menempatkan jaksa sebagai pemilik perkara dan memberinya hak untuk menuntut atau tidak menuntut, menjadi dasar dalam penegakan hukum di Indonesia, serupa dengan negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis. DPA, dalam konteks ini, berfungsi sebagai instrumen hukum acara untuk menangguhkan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu,” kata Prof. Syukri.
Menurut Prof. Syukri, penerapan DPA melibatkan dua tahap utama: Evidential Stage dan Public Interest Stage. Pada tahap pertama, jaksa mengevaluasi apakah bukti sudah cukup, hanya bukti permulaan yang ada, atau ada kemungkinan pelanggaran berkembang lebih lanjut berdasarkan bukti permulaan. Tahap kedua adalah penilaian kritis di mana jaksa mempertimbangkan apakah kepentingan publik lebih baik dilayani melalui DPA daripada melalui penuntutan pidana.
Prof. Syukri juga menyoroti peluang dan tantangan penerapan DPA. Peluangnya mencakup efisiensi peradilan, memungkinkan korporasi untuk tetap beroperasi, dan memulihkan kerugian korban. Namun, ada tantangan serius, seperti persepsi DPA sebagai bentuk “corporate impunity” yang memungkinkan perusahaan menghindari hukuman. Tantangan lainnya adalah sulitnya melacak aset hasil kejahatan, terutama yang disembunyikan atau berada di luar negeri, karena memerlukan instrumen hukum internasional seperti MLA dan perjanjian bilateral.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, kewenangan penuh harus diberikan kepada Kejaksaan. Persetujuan DPA tidak perlu melalui pengadilan untuk menghormati prinsip Dominus Litis,” kata Prof. Syukri.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Prof. Syukri menyarankan Kejaksaan Agung membentuk tim independen untuk memantau pelaksanaan DPA. Contoh kasus di Inggris, seperti kasus Standard Bank, Rolls-Royce, dan Airbus, menunjukkan bagaimana DPA telah berhasil menangani korupsi global yang kompleks sambil tetap memungkinkan perusahaan untuk bertahan dan mereformasi diri. (*)









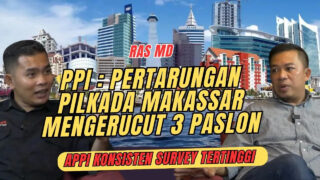

















Tinggalkan Balasan